Kristal-kristal Langit
Hujan turun
deras sekali sore itu, yang ku lihat hanya pandangan yang semakin kabur oleh
warna putih yang tercurah dari langit. Untunglah angin tidak terlalu kencang dan
petir tidak menyalak-nyalak seperti biasa sehingga aku masih berani berlari
menembusnya. Perlu kamu tahu, Kawan.. di Kampungku itu hujan, angin dan petir
seperti Aku, Rizal, Anggara, Gusti dan Wawan di SMPN 12 Bogor. Tidak semua orang mengenal kami tapi mereka sering
berasumsi kami selalu bersama-sama.
Kalo
kamu masih mencoba menghitung jumlah kami yang tidak persis tiga orang seperti hujan,
angin dan petir maka sebaiknya kamu mulai menyadari bahwa cerita ini hanya
FIKSI semata. Andai ada yang dirasa sama maka mungkin kita memang melalui masa
remaja yang sama merananya.
Wawan
adalah petirnya, suaranya memang tidak garang seperti petir, hanya karena
badannya yang paling tinggi dan kekar di antara kami. Kehadirannya cukup
memberi efek menakutkan bagi yang lain, terutama yang tidak mengenalnya baik. Wajahnya
yang sebenarnya ganteng itu tidak mampu menutupi kekurangan di kepalanya yang
sengaja dieksplorasi oleh para hater.
Rupanya sebiji bisul akibat salah makan saat kelas 1 SMP membuat dia menghadapi
masa remaja yang berat, si Pitak
demikian dia dipanggil sepanjang masa itu membuat kepalanya selalu tertutup
topi.
Tapi tahukah
kamu apa yang paling menyebalkan baginya tentang itu, Kawan? Yaitu saat dia
mencoba peruntungannya untuk menyatakan perasaan cinta monyetnya kepada seorang
dara tetangga kelas melalui selembar surat cinta. Si Dara pujaannya tak
mengenal nama pengirim yang tertulis wangi di sampulnya sampai teman
sebangkunya menyebutkan dengan terang benderang.
“Eta si Pitak budak kelas 2 B tea!” (itu
si Pitak anak kelas 2 B - Basa Sunda). Seketika hancurlah hatinya.
Anggara
dan Gusti seperti angin, mereka tidak punya apapun untuk diceritakan. Maaf bukannya
aku tidak sopan dan tinggi hati, tapi dalam kehidupan nyata Tuhan memang terlihat
memilih orang-orang tertentu untuk jadi no
body. Bukan karena mereka tidak berharga tapi semata karena mereka belum
menemukan kondisi yang tepat. Di masa SMP mereka tidak ganteng, tidak pintar
olah raga, tidak pintar di kelas dan bukan juga anak orang kaya. Anggara dan Gusti
itu dianggap angin lalu oleh teman-teman kami, tidak pernah dimasukkan namanya
dalam kertas gulungan pemilihan Organisasi kelas selain daftar piket, tidak
diingat oleh dara cantik kelas berapapun dan kalau bukan karena badge lokasi di lengan kanannya Bapak
Ibu guru mungkin saja tidak ingat kalau mereka pernah hadir di kelasnya.
Tapi tidak
bagiku, entah karena aku pada dasarnya tidak memiliki apa-apa sehingga memiliki
teman menjadi hal yang sangat berarti. Perlahan setelah aku menjadikan
mereka sahabat aku pun mulai melihat kelebihan-kelebihan mereka dan karenanya
aku senantiasa membutuhkannya. Paling tidak mereka tidak pernah
mempermasalahkan pekerjaan sampinganku sebagai Tukang ojek atau Pedagang
asongan di Pasar di hadapan anak-anak remaja sok kaya. Maka jika hari ini kamu membuka-buka buku angkatan dan
melihat beberapa orang yang tidak kamu kenal lagi namanya, mungkin merekalah Angin itu.
Saat itu mereka bukan siapa-siapa tapi hari ini mungkin saja mereka kaya luar
biasa, sukses berbisnis atau menjadi penemu hebat. Lalu kita yang berpapasan dengan
mereka dan menyapa dengan akrab harus menelan kecewa.
“Kamu siapa yah?”
Sang Angin itu hanya menengok sebentar lalu berkata lewat sorot mata dan
senyuman keringnya sebelum benar-benar berlalu.
Lalu
siapakah yang kehadirannya selalu membasahi hati dan menghadirkan kesejukan
seperti hujan?
Tentu
saja Aku dan Rizal. Hehehehe….
Tolong jangan
tersinggung lagi, Kawan! Ini cerpen tulisanku yang aku upload di blog pribadiku, maka biarkanlah aku menulis semauku.
Kalau kamu tidak setuju silakan berhenti membaca!
Eh, maaf… aku engga serius kok, jangan ditutup halaman
blognya yah! Baca dulu sampai selesai Okey!
Rizal dan Aku
sama-sama anak Betawi kampung di antara orang-orang Sunda di Bogor, tentu bukan
hanya kami, ada puluhan anak-anak Betawi kampung yang datang dari sekitaran
Cilebut - Bojong Gede untuk bersekolah di Bogor. Selain itu kami ternyata juga
sama-sama sering disebut namanya karena terlalu sering di tulis namanya di tiga
besar kelas. Rizal sangat koleris, popular
wanna be, di mana ada keramaian dia kan masuk dan mencoba peruntungan di
dalamnya. Tak peduli suaranya hanya cocok membawakan sholawat badar dia selalu menyumbangkan
lagu. Badannya yang tidak tinggi itu juga tidak menghalangi semangatnya bermain
basket, sepak bola ataupun bela diri.
Mungkin menurutmu
kami bosan mendengar dia selalu dipanggil untuk acara ini dan itu, tapi
sebenarnya kami menyukai sifatnya itu, dengan pengorbanannya kami selamat dari
hal-hal memalukan di depan orang banyak. Jadilah kami rajin menyorakinya “RIZAL…RIZAL…
RIZAL…” sayangnya itu bukan bentuk dukungan tapi lebih kepada penjerumusan!
Aku tentu juga
hanya cocok membawakan sholawat badar
tapi aku sangat tahu diri, aku hanya bernyanyi di saat sepi, di dalam hati, sambil
menulis puisi atau cerpen seperti ini. Badanku tidak setinggi Wawan atau
sependek Rizal tapi aku konsisten dengan satu olah raga saja, Bela diri. Konon wajahku
yang terlihat melas dan badanku yang kurus membuat pelatih-pelatihku tidak tega
untuk tidak meluluskanku dalam tiap ujian kenaikan tingkat sabuk. Dan itulah yang
membuat aku jadi satu-satunya siswa SMP berkualifikasi instruktur muda saat yang
lain masih belajar kuda-kuda.
Aku menyukai
semua jenis pelajaran dan cukup berprestasi di semua lini kecuali Kesenian dan
Olah raga tapi ada satu cerita yang tidak akan aku lupa. Di kelas 3 guru bahasa
inggris kami itu adalah wanita berkerudung yang sebenarnya cukup cantik, tapi karena
dia mengajar bahasa inggris seperti melatih bela diri maka aku sering mengantuk
di kelasnya. Saat itulah, saat aku sedang menguap karena diserang kantuk hebat dia
mendatangiku tiba-tiba.
“Kamu mengantuk,
Har?” matanya tajam menatapku kejam.
“Iya, Bu…”
sambil meringis tentu saja.
“Kenapa kamu
bisa mengantuk?” Dia melunakkan suaranya untuk menjatuhkanku.
“Saya bosan, Bu”.
Entah apa yang ku fikirkan saat mengatakan itu.
“Kerjakan saja
LKS (Lembar Kerja Siswa)mu sampai selesai jika kamu bosan melihat saya!”
Nadanya meninggi.
“Sudah selesai,
Bu.” Aku menunduk takluk.
“Kerjakan juga Bab-bab
yang lain, soal-soalnya masih banyak, kalau perlu satu Catur wulan ini kamu
garap semua, kamu kumpulkan di meja saya lalu setelah itu selesai kamu boleh
istirahat.” Kali ini nadanya tenang karena sudah merasa menang. Lalu akupun
berdiri, menaruh bukuku di mejanya dan keluar dari kelas.
“Silakan
diperiksa, Bu. Sudah dari kemarin LKS Bahasa Inggris ini selesai saya kerjakan.”
Dan aku lihat
dia terbengong sambil membolak balik LKSku. Sorenya dia mengembalikan LKS itu
sambil tersenyum manis sekali. Dan bukan hanya dia yang tersenyum manis sore
itu, Wawan, Gusti, Rizal dan Anggara tersenyum lebih manis karena mereka jadi
tahu kalo selama satu Cawu ini mendapat contekan gratis. Sejak itu aku tak
pernah melihat LKS Bahasa inggrisku itu lagi, konon dia sudah berkelana ke
semua ruang kelas dan keluar masuk tas siswa siswi kelas 3. Tapi yang paling
aneh adalah sejak hari itu aku tidak mengantuk di kelas bahasa inggris lagi.
Hujan masih
cukup deras saat butirannya semakin menyakitkanku, rupanya hujan yang putih itu
berubah menjadi hujan es. Wajahku perih saat butiran-butiran Kristal langit itu
mendarat tepat di sana, mataku yang sedari tadi sulit melihat jelas semakin tak
memungkinkan untuk dibuka. Awalnya aku kira dengan absennya angin dan petir
akan cukup aman bagiku mengambil jalur pintasan. Lewat jalur itu aku bisa
menghemat waktu sampai setengahnya dari yang biasa kita lewati kalau
menggunakan jalan utama kampungku. Tapi di jalur pintasan itu ada pohon-pohon
tinggi, jalanan berlumpur becek, jembatan dari sebatang pohon kelapa di atas
sungai yang sedang banjir dan aliran air keruh di tengah jalan dari kebun yang
lebih tinggi. Kalau cuaca begini kami tidak berani melewati jalur pintas itu
takut ada pohon yang tiba-tiba roboh, terpeleset di jembatan apa lagi kalau sedang
musim petir. Apalagi dengan adanya es-es ini aku terpaksa mengambil jalan memutar.
Nafasku memburu
dan kakiku tak kurasakan lagi letihnya. Aku baru saja mengkristakan hatiku
dalam satu tujuan di ujung jalan, aku ingin jadi pelaut. Wawan membawakanku
selembar selebaran sekolah kejuruan pelayaran, dia sudah menyurvei lokasinya dan
memiliki teman yang sudah bersekolah di situ. Aku terlalu gembira hingga tak
bisa lagi merasakan lelah dan bahayanya berlari di cuaca seburuk itu. Yang ku
tahu hanya aku akan meminta izin orang tuaku dan mulai belajar berenang. Masalah
ujian masuk fisik tentu tidak masalah karena latihan bela diri cukup berhasil
menempaku.
Sudah lama aku
ingin berpetualang keliling dunia, lepas dari kampung yang semua penduduknya berbicara
bahasa betawi, memasak makanan yang sama, tinggal di rumah dengan bentuk yang
sama dan bahkan menikah dengan pasangan dari kampung yang bahasanya sama. Semua
kegilaan itu adalah kesalahan Apotik SEJAHTERA di bilangan Jalan Pengadilan
Bogor, setiap tahun mereka selalu memberi kami kalender berisi gambar-gambar
pemandangan luar negeri yang Indah, gunung bersalju, pantai berpasir putih atau
hutan tropis yang eksotis. Jika cuaca cerah dan awan-awan menggumpal di langit
biru sering ku khayalkan diriku terbang melintasi awan dan mengobrol dengan
orang-orang eskimo, menangkap ikan di Sungai Rhein atau berlatih Cross country di Pegunungan Rocky. Dan begitu
melihat selebaran sekolah pelayaran itu seolah laut sudah terbentang dan kakiku
tinggal melompat ke buritan. Semua tampak begitu Indah dan sempurna di benak
seorang remaja.
Saat akhirnya
tiba di rumah, ku lihat ibuku yang kaget melihatku basah kuyup. Ibu sedang
hamil tua dan aku tidak ingin menyusahkannya, jadi aku tidak mengeluhkan
apa-apa. Padanya aku berbohong kalau aku nekat menerobos hujan karena lapar yang
tidak tertahan. Ibuku tentu sudah menyiapkan semuanya, nasi dan lauk pauk
sederhana sudah menungguku di meja makan. Aku makan dengan lahapnya walau
hatiku sudah terombang ambing goyangan kapal khayalan.
Malamnya sambil
melipat-lipat ujung baju ku ceritakan pintaku pada Ayah. Aku hanya bercerita tentang betapa bagusnya sekolah pelayaran itu tanpa secuilpun menyinggung betapa inginnya aku berpetualang keliling dunia. Ayah mendengarkanku
sampai tuntas lalu dengan nafas berat tertahan dia bertanya:
“Kalau kerja di
Kapal nanti sembahyangnya bagaimana,
Aa?”
Akupun sudah
tahu cerita-cerita kabar burung tentang buruknya pergaulan di kapal dan
bebasnya pergaulan mereka di pelabuhan. Ayah meringkas ketidak setujuannya
dalam satu kata sakral untuk orang betawi : Sembahyang.
Mempertanyakan bagaimana aku akan sholat bukanlah pertanyaan seputar fiqih
sholat di atas kapal seperti bagaimana bersucinya, kiblatnya dll, ini tentang
ketidak setujuan seorang ayah kepada anaknya yang didasari oleh ketakutan akan
hilangnya agama si anak. Aku sepenuh jiwa memahami kekhawatiran itu, sepenuh nafas
menyetujuinya tapi separuh hati juga pecah bersamanya. Sama seperti Kristal-kristal
langit yang menerpaku sore itu, setelah begitu memukau, dia menyakitiku lalu
hilang menguap begitu saja.
Mei 2003
Ku
masukkan semua baju, sepatu, alat mandi dan beberapa lembar uang lima puluh
ribuan ke dalam tas besar itu. Ibuku mematung di muka pintu, ada kesedihan
tertumpah melihat bujangnya akan pergi. Jadi aku diterima bekerja di sebuah
perusahaan Grup BUMN di sekitar Pelabuhan Merak Cilegon dan harus mengikuti
pendidikan beberapa minggu sebelum ditransfer ke Lokasi lain sepanjang Pantai Jawa.
Cilegon bukanlah tempat yang ku inginkan dalam doa, cita-cita maupun khayalan
kecilku. Walaupun lokasi plant di
tepi pantai tapi Cilegon terlalu panas dan berdebu. Padahal aku inginnya
bekerja di tepi pantai yang Indah bersama burung camar dan tinggal di kaki
gunung yang sejuk berselimut kabut. Rupanya hingga mendapat pekerjaan dan harus mandiri, sisi
kekanakanku masih saja ada.
Ku
sapu semua keraguanku meninggalkan Bogor bersama semua kenangan yang sebentar
lagi akan benar-benar menjadi kenangan. Satu demi satu keraguan datang menggodaku untuk tetap tinggal di Bogor. Saat bis membawaku melintasi tol Jagorawi,
satu demi satu kenangan berhamburan. Semua petuah dan ucapan selamat jalan dari
senior, Paman, Bibi, Ustad, rekan santri dll silih berganti terngiang di
telingaku. Tapi hanya ada satu kalimat yang terdegar jelas dari suara parau
ayahku sebelum melepasku di Terminal Baranang siang.
“Jangan
lupa sembahyang ya, A!”
Pasuruan, 12 Januari 2015
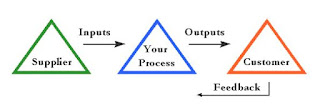

Such a great story. Touching. :)
BalasHapusThanks, Sis
Hapus