Lipsing
“hayya ‘alas sholaaahhh..” tanganku gemetar memegang mikrofon.
Gemetaran membuat aku lupa pada bait selanjutnya, anak lelaki kurus di
sebelahku yang juga gemetaran berbisik tak jelas membantuku mengingat-ingat.
“habis ini apaan?”
“falaaah, falaah, belakangnya diganti falaah, To.”
Kami berdua menyadari
dialog itu terdengar seantero kampung dari speaker
yang dipasang di puncak menara. Kami berdua juga sudah bisa membayangkan si
Abah pengurus masjid sedang memasang tampang seram sambil berjalan cepat ke
masjid. Maka saat bait terakhir adzan selesai diteriakkan kami sepakat
melarikan diri tanpa menunggu sholat ashar berjama’ah didirikan.
………………………..
Orang Betawi kampung
seperti kami memiliki sebutan yang berbeda untuk dua jenis sekolah yang kami
jalani. Sekolah umum yang mengajarkan ilmu duniawi seperti IPA, matematika, IPS
dan PMP disebut sekolah laten.
Sedangkan sekolah tempat kami belajar ilmu ukhrowi
disebut sekolah agama atau di sebut juga madrosah.
Di sekolah laten kami biasana jarang
berpindah-pindah, sekali masuk akan istiqomah dijalani sampai selesai. Selesai
di sini tidak selalu berarti lulus, ada kalanya kami lebih terpanggil membantu
orang tua yang berekonomi lemah dengan bekerja sebagai kuli di Pasar, atau bagi
yang putri menemukan seorang suami yang bisa menafkahi bisa juga menyebabkan
selesai sekolah lebih cepat. Tak jarang surat undangan dari seorang siswinya
membuat Guru kami menghela nafas.
Jika boleh ku ceritakan
seorang siswi yang ceria wajahnya, cerdas pula otaknya dan bintang kelas di
sekolah kami. Dia adalah andalan dalam lomba cerdas cermat dan sering mewakili
guru kami membantu kami menyelasaikan PR yang terasa sulit. Kakak kelasku itu
sangat sering jadi buah bibir di ruang guru, dan tak ada sedikitpun celanya di
mata Bapak Ibu guru. Namun menjelang kelulusannya ada kabar dia menarik hati
seorang duda kaya, kabar itu segera merebak dan dituntaskan dengan dikirimnya
sebundel surat undangan ke sekolah. Aku tinggal sekampung dengannya, dan
rasanya kami juga kehilangannya, satu SD membicarakannya dan entah kenapa ada
rasa malu menggelayuti hatiku.
Selepas sekolah laten siangnya kami sekolah agama, tempatnya
bisa berbeda-beda. Rekan sekelasku di SD tidak semuanya di sekolah agama yang
sama, bahkan tidak semua ikut sekolah agama, tergantung bagaimana visi orang
tuanya. Bagi Ayahku yang Pegawai negeri itu, melepaskan anaknya ke dunia nyata
dengan ilmu umum saja sama dengan memesan kunci pintu neraka. Maka ayahku yang
juga konon mantan santri kalong itu
sangat sigap menyerahkanku ke madrosah,
sesaat setelah aku naik kelas 2 SD aku langsung dicengkiwing (dituntun dengan sangat keras) ke pintu Madrasah Diniyah
di kampung sebelah untuk belajar agama selepas dzuhur. Bukan hanya itu, selepas
maghrib kami masih harus mengaji ke majlis ta’lim lainnya. Ayah juga begitu,
memasrahkanku kepada seorang Ustadz muda untuk dibimbing lebih privat lagi
selain dua sekolah di atas.
“Kalo si Aa kaga mau belajar, sabet wae, Mang! (kalau anak ini tidak mau belajar pukul saja,
Paman!) ” begitu katanya kepada Mang Ajat yang walaupun pamanku sendiri namun
tidak menyia-nyiakan wasiat tersebut.
Namun sebagaimana
lazimnya lembaga yang dibangun dengan keikhlasan semata, banyak madrosah yang gulung tikar di tegah
jalan. Sebenarnya SPP di sekolah agama sungguh tak mahal, tapi entah kenapa ada
sebagian orang-orang tua betawi masa itu lebih takut kehilangan rokok sebungkus
dari pada berinfak lebih kepada para
asatidz yang membesarkan anak-anaknya. Jadilah bagi sebagian orang SPP
sekolah agama lebih sensitif dari harga BBM, jika harga BBM dinaikkan orang
akan ramai berdemo tapi tetap antri di SPBU namun jika SPP dinaikkan mereka
bersungut dalam diam dan berhenti mengirim anaknya mengaji. Maka saat satu madrosah mengalami kemunduran Ayahku
langsung bermanuver memindahkan aku ke madrosah
yang lain. Untunglah pada masa itu jumlah ustadz dan madrosah masih cukup banyak, walau kami tidak pernah tahu apakah
keikhlasan mereka juga masih tersisa cukup banyak.
Penggalan cerita adzan
yang ku ceritakan di awal cerita sepertinya terjadi saat aku kelas 3 SD. Adalah
Ayahku provokator di balik itu semua, atau dalam hal ini beliau bisa kita sebut
sebagai motivator. Perbedaan dua kata itu menurutku terletak pada tujuannya,
provokator menginginkan kerusakan bagi si korban agar dia bisa mengail di air
keruh, sementara motivator berharap dari keruhnya air bisa keluar kemurnian
yang bermanfaat bagi si korban. Tapi bagi korban, mereka akan sama-sama
menderita, bagaimanapun akhir ceritanya, apapun nama sebutan pelakunya. Ayahku
yang saat itu memperhatikan adzan ashar di masjid kampung kami sering kali
telat dikumandangan memandang perlu mendidik generasi baru.
“Aa belum bisa adzan,
Pah.” Aku menghindar sebisa-bisanya.
“Ajakin si Agus buat nemenin, entar dia yang ngasih tahu
kalo Aa lupa.” Begitu jawabnya.
“Malu ah, sekampung
denger semua. Entar Aa dikatain temen-temen.” Aku menegaskan peer pressure yang dialami anak kecil
sebagai pembelaan.
“Emangnya kalo dikatain itu nempel di badan ya? Lagi juga paling berapa lama mau ngata-ngatain orang, lelaki mah jangan terlalu perasa!”
Dan terjadilah tragedi
ashar itu, kawan.
Sudah diduga,
teman-temanku langsung ramai komentar, aku jadi sangat menunduk kalau berjalan.
Parahnya aku jadi tidak berani ke masjid lagi, takut benar bertemu si Abah
ta’mir. Namun di situlah aku belajar perbedaan jenis-jenis motivator. Ada
ayahku yang cenderung radikal dn tentu aku jadi mengetahui ada juga yang lembut
dan menentramkan. Di madrosah ada
seorang ustadzah yang rupanya mendengarkan kami adzan ashar itu, Kak Ningsih
kami memanggilnya, di kelasnya dia membahas itu sekilas.
“Alhamdulillah, di sini
ada yang sudah berani adzan di masjid. Memang masih ada salahnya, tapi wajar
untuk pemula, Kakak juga ngajar ini masih banyak salahnya kok”. Namaku tidak
disebut, tapi hatiku menghangat bersama wajahku yang memerah tertunduk dalam
walau jiwaku berbunga-bunga.
“Kakak harap akan
muncul Muazin-muazin baru yang tidak berhenti jadi muazin, lalu jadi Imam
masjid, lalu jadi Mubaligh, lalu jadi
Ulama besar. Semua diawali dari hal yang kecil seperti adzan ashar”. Dan sore
itu aku bertekad untuk adzan sesering mungkin dengan atau tanpa disuruh Ayah.
Ayahku tentu senang aku
menjadi semakin sering ke masjid, suara adzanku semakin sering terdengar dan
semakin baik. Motivasi bisa datang dari jalan yang mungkin saja kita tidak
sukai, bahkan kita bisa menganggap semua hal adalah motivasi. Sebenarnya
kemiskinan bisa memotivasi kita agar rajin bekerja, nilai yang jelek memotivasi
kita lebih kreatif dalam belajar, kegagalan memotivasi kita untuk mengevaluasi
diri, dan lain-lain. Atau sebaliknya, apapun bisa kita anggap sebagai
demotivasi. Kita menyerah saat nilai jelek dan terlena saat nilai bagus, kita
menyalahkan takdir saat miskin dan berpoya-poya di masa kaya dan kita bisa
menuliskan apapun, Kawan. Kata Syekh Yusuf Al-Qordhowi di suatu petikan yang
aku baca bahwa kelak Allah SWT di Akhirat tidak akan bertanya kenapa kita
gagal, tapi bertanya kenapa kita tidak berusaha.
Ayahku sering sekali
memotivasiku keluar dari zona nyaman. Kalimat lelaki jangan cengeng, kalau
ragu jangan dikerjakan, bukan
sekedar ucapan atau bacaan di buku bahasa Indonesia. Beliau bahkan pernah meninggalkanku di acara
uji nyali untuk membuktikan bahwa setelah kesulitan akan ada kesenangan. Ayahku
memang radikal untuk beberapa hal.
Ceritanya mungkin saat aku
kelas 3 SD diajak ke sawah untuk mengatur pengairan kebun kami di areal
pesawahan yang luas sekali. Areal itu membentang dari Kampung ku di sebelah
timur hingga Kampung Cimanggis di sebelah barat, jalan KH Soleh Iskandar di
sebelah selatan dan Kampung Kencana di utaranya. Di area yang seluas itu kebun
kami sebenarnya hanya setitik noktah dan itupun adalah milik saudara, kami
hanya diminta bantuan menggarapnya saja. Saat itu malam jumat dan di televisi
Dunia Dalam Berita sudah dimulai.
Setelah berjalan
beberapa menit di tengah kegelapan malam kamipun tiba di persimpangan anak
sungai. Ayahku langsung bekerja memacul untuk mengalirkan air ke kebun kami dan
aku bertugas menyinarinya dengan senter. Beberapa lama kemudian ayah teringat
kalau goloknya tertinggal, lalu dengan pertimbangan akan merepotkan kalau aku
ikut pulang kembali maka beliaupun meninggalkanku sendiri di tengah malam,
tengah sawah, beralas rumput beratap bintang dan beriring suara jangkrik. Menit
demi menit berlangsung begitu lama dalam penantian, bintang gemintang begitu
indah tapi hatiku penuh was-was. Bayangan film-film horror tahun 80an tentang
Tukang sate yang didatangi seorang gadis cantik berusaha ku buang jauh dari
kepalaku. Aku ingin berlari pulang tapi akalku mengatakan itu akan berakhir
jauh lebih buruk, aku bisa saja terjatuh ke sungai lalu hanyut atau tersesat
sampai pagi. Maka di situlah aku entah untuk berapa lama, duduk bersimpuh di
pinggir saluran irigasi, berharap Ayah segera datang.
Setelah Ayahku datang
dan membereskan pekerjaannya di sana kamipun pulang tanpa ku ucapkan sepatah
katapun. Ada perasaan bahagia begitu kakiku menginjak lantai tanah rumah kami.
Rumah kami yang belum dicat, lampu listrik temaram dan TV hitam putih harta kami
satu-satunya nampak begitu indah. Tapi bukan itu saja bagian yang paling
menyenangkan dari malam itu. Setelah membersihkan diri seadanya di kamar mandi
ayah memanggilku untuk menonton TV. Dan film yang diputar malam itu berjudul
Aladdin, dibintangi oleh seorang anak muda bertahi lalat yang kurus namun
energik. Rasanya film itu melengkapi kegembiraanku pulang ke rumah.
………………………………………………….
Lapangan Olah raga SMAKBo
sekitar pertengahan 1999.
Maka berdirilah aku
hari ini berkepala botak, menyanyikan lagu sendu di depan api unggun penebusan
dosa, melingkari api bergandengan tangan dengan anak perempuan yang rambutnya
dikuncir dua dengan pita warna coklat putih dan anak laki-laki yang serupa
denganku. Acara api unggun ini mengakhiri penderitaan kami di pekan orientasi
teraneh seumur hidupku. Acara yang memaksa kami mengukir di atas ubi rebus,
menghitung biji kacang ijo, meminta tanda tangan kepada senior yang angkuhnya
bukan kepalang dan yang paling memuakkan adalah menundukkan kepala saat
berjalan dari satu ruang ke ruangan yang lain.
Tapi tidak semua hal di
sana menyebalkan, di acara itulah aku jadi bisa menyanyi dengan benar. Paduan
suara adalah kegiatan wajib bagi kami, aku yang di SMP sering menyanyi ditempa
habis-habisan oleh senior yang tampangnya seram hingga yang tampangnya pasrah.
Dan setelah berhari-hari latihan keras dari pagi hingga sore aku merasa suaraku
sudah seindah Julio Iglesias atau semirip Boy zone dalam paduan suara. Tapi
anehnya semakin keras aku menyanyi, semakin tinggi kepercayaan diriku, selalu
saja ada senior datang mendekat. Senior yang berwajah kejam hingga yang
berwajah sendu, mereka mendekatiku setelah menyanyi dengan satu pesan yang
sama.
“Maneh mah lipsing wae atuh!” (kamu itu menyanyinya lipsing saja!)
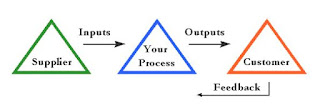

Komentar
Posting Komentar